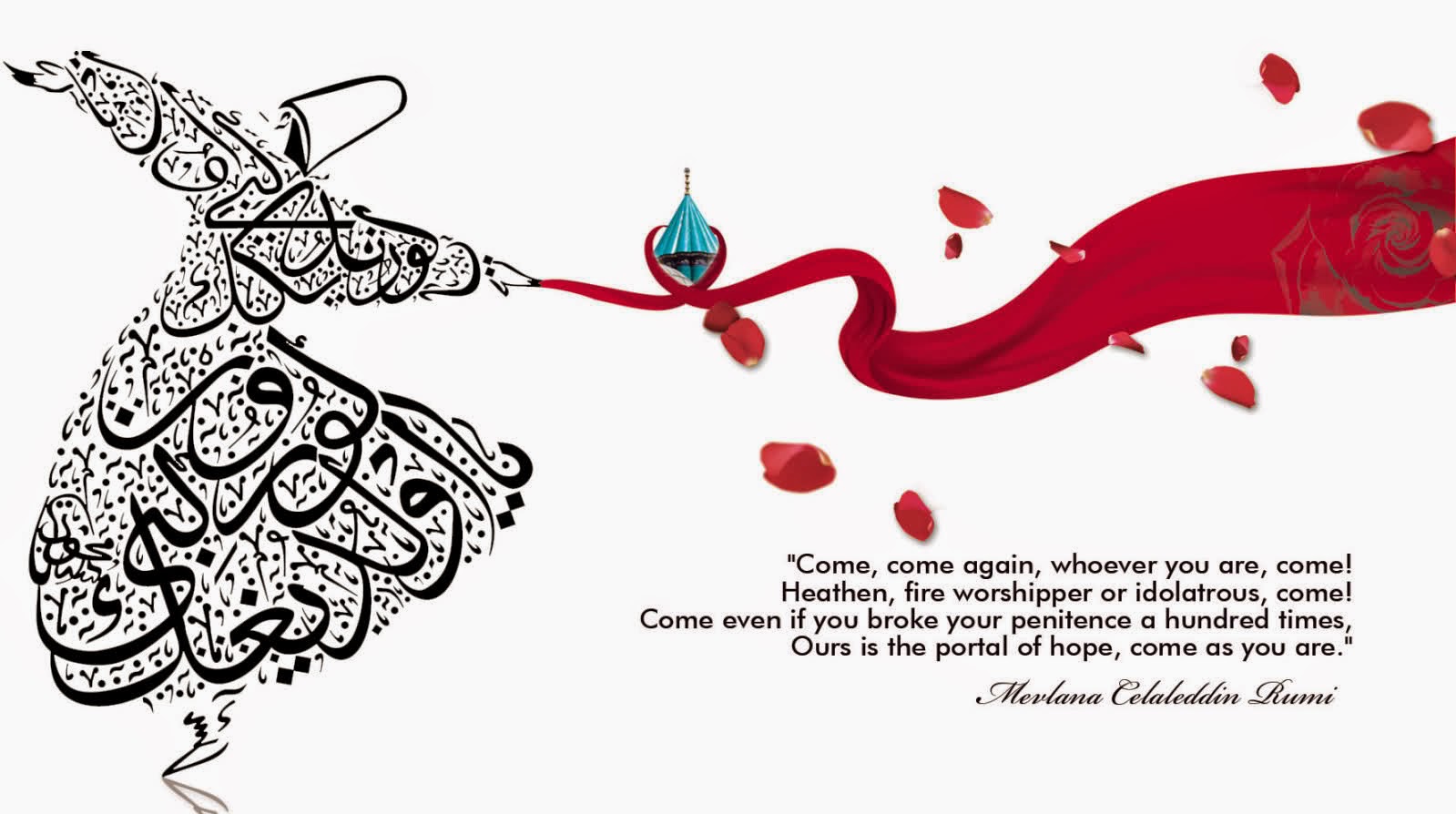Potretmu membisu di kamar itu
Keinginan untuk bebas tanpa ikatan musnah
Tertembus paku-paku baja yang mematri di sekelilingmu
…
(Potret Bisu, Jefri Widodo)
Potret, paku-paku baja, dan ikatan dalam puisi ini—hemat saya—sangat
menarik untuk dicermati. Adakah ketiganya “ikatan” yang saling mengikat
kuat atau sebaliknya, saling mencengkeram? Jefri Widodo, melalui
perenungannya, berhasil mengungkapkan kegundahan tentang “potret” yang
membisu di ruangan nan anggun dalam koridor pigura. Ya, potret yang
gelisah. Potret yang ingin merangsek keluar dari pigura yang dijaga
dengan kokoh oleh paku-paku baja.
Potret, yang anggun dalam pigura, bagi pemasangnya tentu memiliki
arti. Potret adalah simpanan kabar yang ingin dikenang. Tentunya sang
pemasangnya menaruh di tembok bukan ingin memasung kehendak potret itu
sendiri, tetapi sudah semestinya begitu. Namun, boleh jadi , potret yang
mengalami hal demikian berkendak lain: ingin bebas dan tak ingin
menjadi kabar yang dikenang. Ia ingin bebas, sebagaimana “peristiwa”
yang telah dilaluinya.
Potret memang bisu, tak bisa bicara secara lahiriah. Dan bisu adalah
bentuk sikap lain dari wicara. Bisu bukan berarti tak ada hal yang bisa
diungkapkan. Justru dari yang bisu melahirkan beragam tafsir. Dari
kebisuan terkadang lahir beragam ilmu bagi yang mau menimba darinya.
Jerfi Widodo baru sekelumit “menciduk” air sumur dari berbagai sumber
kebisuan yang ada di sekitarnya. Hal yang sedikit itulah justru menambah
cakrawalanya berpikir. Menambah daya cercap tentang lingkungannya.
Bila kita simak: sekitar kita kebanyakan bisu atau sekedar dibisukan.
Jalanan, hutan, sungai, rakyat kecil, dan bahkan kitab suci adalah
bagian dari yang bisu. Semua itu membutuhkan kecakapan membaca dari
pihak yang tak bisu. Semua itu memerlukan interprestasi yang matang dan
jeli. Sebab, interprestasi membutuhkan berbagai ilmu agar mempunyai
makna yang tepat.
Kegagalan penguasa dimulai dari kegagalan membaca yang “dikuasai”.
Sebab, yang dikuasai biasanya tak banyak bicara, yang bisu karena
berbagai alasan. Seorang guru gagal menyampaikan ilmu kepada sang murid
karena menempatkan murid “yang bisu” dan hanya perlu dijejali dengan
beragam teori. Tanpa mau mendengar uneg-uneg yang tak
tersampai. Kerusakan alam diakibatkan membabi butanya eksploitasi yang
menganggapnya hanya sekedar bahan jarahan, bukan makhluk yang selayaknya
bisa berbicara. Amburadulnya ekonomi terjadi ketika pelakunya hanya
menggunakan “ satu telinga”: untung-rugi.
“Potret Bisu”, dipilih mewakili dari sekian puisi yang terangkum
dalam antologi dua belas penyair Teater Magnit Ngawi, tak lain bentuk
sikap “belajar” terhadap yang bisu. Saya lebih senang menyebut sikap
“belajar” karena dalam hal ihwal dalamnya ada gerak naik-turun. Ada
semangat. Ada rasa untuk terus mencari, meski jatuh bangun. Sikap
belajar adalah sikap berpuasa—dan penyair adalah manusia yang terus
berpuasa. Sikap yang berhasilnya kanti laku. Puasa adalah upaya
memeka radar-radar yang dimiliki manusia untuk menangkap
frekuensi-frekuensi halus atau yang tak tersentuh radar kebanyakan. Dan
frekuensi-frekuensi inilah yang sering dianggap bisu.
Antar-penyair tentunya memiliki kepekaan tersendiri terhadap obyek
yang disampaikan. Batu di mata penyair bisa mengandung beragam makna.
Meragamkan berbagai tafsir tentang batu itu sendiri. Semakin beragamnya
tafsir tentang batu yang dilakukan para penyair tentunya semakain
menambah hazanah keilmuan, dan menghidupkan batu itu sendiri, yang dalam
ilmu hayat disebut benda mati.
Ellisa Olivia A, mencoba memotret yang bisu dengan sajak “Oleh
Rindu”nya. Sajaknya sebenarnya berisi kepiluan tetapi ia cepat
mengolahnya sehingga tak terlihat pilu. “Ketika burung-burung gugur
dari kepaknya dan masih mengepak ke langit/ ketika bunga-bunga luruh
dari wanginya dan masih semerbak ke langit…” jika disimak ada
sesuatu yang akan terbaring kalah namun dalam prosesnya itu masih ada
sisa-sisa tenaga agar kekalahannya itu tidak sekedar kekalahan tanpa
nilai. Ia percaya bahwa rerentuhan, pudarnya keharuman, birunya laut
yang kini mulai tercemar oleh berbagai kegilaan manusia bisa disatukan
oleh rindu.
Rindu, bagi Ellisa, menjadi nadi gerak hidup makhluk. Sebagaimana
Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan tak lain dibalut dengan
rasa saling merindu. Malam yang cepat melarut ke dalam siang karena ada
rindu. Kemarau yang mengkerakkan tanah, seakan tangan yang menengadahkan
doa-doa agar lekas terguyur air hujan. Rindu pula yang sering jadi tema
sentral kaum sufi melukiskan “ketaataanya” pada Tuhan, bukan karena
terpaksa.
Ada rindu, berarti ada cinta. Hal itu dibuktikan dengan
puisi-puisinya Hanifah Hikmawati. Penyair muda yang masih tercatat
sebagai mahasiswa jurusan Sastra Arab UNS (Universitas Sebelas Maret,
Solo) ini mencoba mematangkan arti cinta dan rindu. Sajak “Hikayat
Al-Hubb”, misalnya, yang terdiri dari tiga sajak tak lain bentuk
pematangannya dalam menangkap arti cinta. Sebagai mahasiswa yang
berlatar belakang bahasa Arab, pembaca mungkin akan menerka jika “Al-Hubb”nya itu pasti cinta kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak. Namun, ia juga tidak melulu mengisahkan percintaan dunia (Hubbudunnya) tetapi menggarap dua wilayah itu secara proporsional. Ia memotret hubb-nya
perjalanan manusia: dari bayi hingga tua dengan segenap
permasalahannya. Terkadang pula ia merintihkan do’a-do’a, kedukaan,
kesukacitaan manusia. Begitu pula, sebagai manusia, ia mengabarkan
tentang Hubb terhadap sesama—yang dalam sajak “Hikayat Al-Hubb” obyeknya memakai kata “mu”.
Ika Friliyana mengambil jalan yang berbeda dari para penyair yang
telah disebutkan di atas. Melalui sajak-sajaknya ia ingin menegaskan
bahwa menghadapi dunia yang semakin gila, dengan berbagai ocehan yang
membisingkan langit haruslah bersikap tegar. Tegar di sini bisa dalam
wujud “tak ambil pusing” dengan berbagai ocehan tadi. Sajak “Jalanan
Ini”, misalnya, bagaimana ia menyikapi berbagai tantangan dunia dengan
keyakinan jika “langkah kakiku” akan melangkah sendiri sampai nanti.
Boleh jadi “nanti” yang dimaksud adalah cita-cita, tujuan dari
langkahnya.
Istichomatul Chosanah mengeksplorasi lebih dalam lagi dengan
sajak-sajaknya. Sajak “Tersangkut Di Sehelai Rambut” adalah media yang
ia gunakan untuk mengintip desah rambut pada tanah. Gerangan apa yang
akan disampaikan rambut pada tanah sebelum ia jatuh padanya? Tak ada
yang tahu. Mungkin ada dialog tawar-menawar antara rambut dengan tanah:
supaya rela menerima ‘kejatuhan’nya. Di lain pihak, dalam sajak
“Sepatu”, ada semacam sejarah panjang tentang alas kaki itu. Sepatu
adalah teman yang setia mengawal perjalanan. Sehingga, tatkala
pemakainya jika kelak mendapat ‘tiket’ surga, ia berharap agar sepatu
yang pernah dipakai pun bisa masuk surga. Sajak ini mengingatkan saya
pada hadist Rasulullah SAW mengenai pencari ilmu. Sebab, di dalamnya di
kabarkan jika manusia pergi mencari ilmu dan mati dalam menempuhnya maka
ia dijamin masuk surga. Bukankah sepatu dan pencari ilmu adalah dua hal
yang tak terpisah untuk saat ini?
Selanjutnya, sajak-sajak Kaha Anwar adalah sajak kegelisahan. Sajak
yang ia tulis dalam dua masa, dan dua tempat yang berbeda. Sajak
“Simpang Sumpol” yang ditulis sekitar tahun 2006 di Sungai Danau,
Kalimantan Selatan adalah kegilasahan tentang keangkuhan tambang-tambang
yang ada di sana. Tambang adalah pundi kekayaan dan seharusnya bisa
mensejahterakan penduduk sekitar ternyata berbeda dengan kenyataannya.
Penduduk sekitar tetap saja miskin, seakan hanya menjadi penonton konvoi
truk-truk “pengangkut batubara. Kegelisahannya itupun ia haturkan
kepada Tuhan—terlukis dalam sajak “Obsesi” dan “Doa yang Kesepian”.
Obsesi yang tak lain keinginan yang selalu menggoda, jika boleh
dipadatkan tak lain adalah doa. Ya, dalam sajak itu ada semacam
menertawakan para pendoa: “Selalu, tiap pagi setinggi tombak kau datang bawa kata yang jemu kudengar…oleh doamu yang tak kunjung tumbuh di tubuh peluh.”
“Pagi setinggi tombak” jika kita menggunakan cara membaca waktu zaman
dahulu tak lain itu waktu dhuha. Dhuha sendiri oleh kalangan umat Islam
selalu dikaitkan dengan waktu yang tepat untuk meminta kelancaran
rezeki. Apabila dalam berdoa di waktu dhuha ini hanya meminta keduniaan
semata tentunya sangat naïf. “Engkau tak akan pernah kaya jika hanya meminta, walau seribu dhuha engkau lakukan, tanpa bekerja”,
mungkin itulah yang ingin Kaha sampaikan lewat sajaknya itu. Begitu
pula dalam sajak “Tuhan” yang ia tulis di Yogyakarta: tak lain wujud
kegundahan. Ia menyimpan pertanyaan yang akan ditanyakan pada Tuhan
tentang nabi-nabi, kitab-kitab, agama-Nya. Sebab, baginya, ada sesuatu
yang belum terjawab meski banyak tafsir-tafsir tentang itu semua.
Sebaliknya, tafsir-tafsir malah menimbulkan justifikasi kebenaran
sepihak, yang meneguhkan bahwa manusia mendahului kerso, kehendak Tuhan.
Waktu sepertinya media yang tepat untuk mengungkapkan uneg-uneg
penyair. Sebagaimana Khotimatul Aminah, dengan waktu ia mengabarkan
detik-detik menuju Ilahi. Sajak “Subuhku”, “Pukul 22.00”, dan “Hening”
tak lain masa penantian bercumbu dengan Tuhan. Masa-masa itu kebanyakan
manusia asyik dengan dengkurannya. Namun, bagi Khotimatul, waktu itu
adalah waktu penantian. Waktu menggelar sajadah untuk bermunajat pada
Tuhan yang menguasai waktu. Waktu untuk mengheningkan kalbu, ketika para
makhluk akan memasuki masa keriuhan aktivitas.
Di lain pihak, Penyair Muhtar S. Hidayat sajak-sajaknya dipenuhi
aroma sosial. Ia ingin langsung bersinggungan dengan keadaan alam
sekitar. Ia menjumput rokok—dalam sajak “Rokok”—dan membelanya. Rokok
sekarang ini dihukum habis-habisan: pangkal segala penyakit. Ia tak
segan-segan meng-counter opini-opini yang sekarang tercipta. Ia
berani menegaskan: Merokoklah sebatang! Sebab, dalam hisapan rokok akan
tercipta baying tentang petani rokok, para buruh rokok yang kebanyakan
perempuan itu. Kenapa rokok yang selalu disalahkan dan diberi cap pada
bungkusnya jika ia sumber biang keladi impotensi dan hipertensi?
Bukankah selain rokok ada produk-produk lain yang lebih berbahaya? Ini
tak lain penzoliman terhadap rokok. Begitu pula dalam sajak “Jati
Blora”, darinya ada kenangan, ada sumber kehidupan bagi warga sekitar
hutan. Sajaknya ini mengingatkan saya dengan desa saya: dahulu, sebelum
waktu subuh usai, beberapa tetangga saya selalu bergegas ke hutan untuk
mencari daun jati. Dari situ ia menjual ke penjual-penjuan di pasar dan
uangnya mereka gunakan untuk membeli beras dan menyekolahkan
anak-anaknya.
Namun, kenyataannya sekarang berbeda, hutan jati menjadi barang yang
sangat dilindungi. Ada moncong senapan yang siap menyalak menegur para
pencari daun jati. Tetapi, senapan itu mlempem, ketika tangan-tangan angkuh manusia kota menghujamkan pisau ke pohon-pohon jati.
Begitu pula dengan penyair Dwi Nur Sukmono, yang masih mengusung tema
sosial dan bernada gelisah. Sajak “Kita Ini Bangsa Kerongkongan” adalah
sentilan telak bagi para pemangku kekuasaan, rakyat, bahkan Tuhan.
Baginya pemangku kekuasan tetap bersikap ndoro yang harus
dilayani. Sedangkan rakyat tak pernah puas dengan gaya kepemimpinan sang
penguasa. Ketidaksinambungan ini akhirnya menciptakan ontran-ontran,
kerusuhan dalam segala hal yang tak kunjung usai. Apalagi Tuhan
menambah kemelut ini dengan kutukan-Nya, yang tak pernah berhenti.
Sajak “Ikan Dulu dan Kini” karya Penyair Susilo tak lain menyikapi
fenomena anak sekolah sekarang. Ada yang beda antara anak sekolah dahulu
dengan kini. Kenapa ia memilih ikan untuk menyikapi fenomena anak
sekolahan tersebut? Ada sebuah hadist yang mengabarkan bahwa ikan-ikan
di lautan, dan sungai akan senantiasa mendokan para pencari ilmu.
ikan-ikan itu setia mendoakan. Hal itu tentunya karena pencari ilmu
tulus niatnya, semata-mata memerangi kebodohan. Namun, boleh jadi niat
itu kini telah berubah. Sekolah, mencari ilmu bukan lagi demi memerangi
kebodohan tetapi mungkin karena mengharap kedudukan setelah lulus.
Sehingga “kemilaunya mutiara ilmu tak lagi diselimuti elok”, sehingga ikan-ikan kini pun berhenti berdoa.
Kekonyolan niat mencari ilmu itupun berimbas pada kekonyolan polah
tingkah. Coba pergilah ke sekolah, atau setidaknya nongkronglah di tepi
jalan yang dilalui anak-anak sekolah dan simak mereka: apa yang bisa
anda bedakan antara jalan sekolah dan catwalk? Tapi, ini bukan
salah mereka semata. Mereka hanyalah imbas dari pihak yang berpengaruh
luas. Dari lingkup yang selalu menebarkan bibit penyakit pada semaian
intelektual, dan pola tingkah mereka.
Tak heran jika Vivi Rocharirin menanyakan realita-realita yang
dialami “barisan pengaku merah jambu” dalam sajaknya “Surat Kecil Untuk
RA Kartini”. Emansipasi, kesepadanan derajat kaum Adam dan Hawa ternyata
masih meleset atau bahkan keliru diterjemahkan: “…Saat payudara dan pahamu kau pertontonkan tanpa rasa malu. Inikah kesetaraan yang kalian inginkan?..”
Vivi pun berharap pada RA Kartini, yang dianggap sebagai pelaku
pertama pengusung emansipasi, agar bangkit lagi. Agar menerjemahkan atau
mewedar kepada kaumnya tentang arti kesetaraan itu. Agar
perempuan—manusia, secara umum—tak terjebak pada pilihan: mana api mana
air. Vivi memang penyair perindu: merindukan perempuan yang benar-benar
empu bukan sekedar empuk (lunak) daging yang sering
dipertontonkan. Begitu pula, ia merindukan tentang masa lalu yang
dianggapnya ada kedamaian. Masa lalu memang menjadi romantisme yang tak
surut dikunjungi, meski itu hanya bekas-bekas yang hampir menyublim.
Sajak “Kota Hilang” tak lain merupakan tanggapannya terhadap kota-kota
besar yang semakin kehilangan ruh lokal widom-nya. Padahal dahulu di
tempat itu tumbuh nilai-nilai luhur yang pernah dituturkan oleh leluhur.
Tapi kini, yang jadi cerita adalah kerlap-kerlip lampu kota, jalanan
yang bising, dan gelak tawa penghuninya di ruang-ruang hiburan.
Ada dua tipe dalam sajak-sajaknya Wahyu Prihantoro. Pertama, sajak-sajak yang mencoba bercumbu intens
dengan alam, tergambar dalam sajak “Tangisan Laut”, “Malam Mati”,
“Bintang Menancap Hati”. Laut, malam, dan bintang baginya adalah media
yang seharusnya digunakan untuk selalu bertafakur, ber-muhasabah
diri di hadapan ilahi. Sebab ketiganya menandakan ada pergantian waktu:
yang datang dan pergi. Ada umur manusia yang kian hari menyusut,
berkurang namun dirayakan dalam pesta ulang tahun. Lewat sajak “Kado
Ulang Tahun” Wahyu mencoba mengingatkan: dalam pesta itu ada sesutau
yang terus pergi dan tak pernah kembali, yaitu umur.
Kedua, sajak-sajak yang berusaha menyurakan tentang keadaan Negara.
Sebagai anak yang tumbuh di alam demokrasi, Wahyu ternyata menemui
bualan-bualan dari para calon pemimpin. Sajak “Suaraku” adalah gambaran
bagaimana kampanye para calon pemimpin hanyalah kamuflase semata. Bak fatamorgana yang menyuguhkan kilaun oase di tengah padang pasir tapi kosong melompong.
Janji-janji yang tak ditepati itulah yang menjadikan negara ini terus
hidup dalam kepura-puraan—seperti yang terlukis dalam sajak “Negara
Palsu”. Semakin lihai berpura, semakin pula makmur hidup seseorang di
negara palsu. Dan kenyataannya, memang kita pun damai dengan beragam
kepalsuan yang ada. Apakah yang dihadapan seorang murid itu benar-benar
guru atau sebaliknya: sales ilmu? Benarkah ia presiden atau
jangan-jangan hanya penguasa partai yang kebetulan saja menerima
kekuasan setelah sekian adegan perebutan itu dilakukan? Benarkah ia
ulama atau jangan-jangan germo macak kyai? Inilah potret negara palsu: yang sudah susah dibedakan lagi karena kita sendiri juga palsu.
****
Akhirnya, puisi memang bukan sekedar gremengan hati. Bukan sekedar kongkalikong
estetika bahasa. Tetapi, puisi memang semacam luapan hati. Ia bisa
berwujud apa saja yang oleh penyair dicoba dipadatkan dalam kata-kata
untuk dikabarkan kepada pembacanya. Meski pembaca itu pun hanya skala
diri pribadi.
Dan, kedua belas penyair muda Magnit itu baru memulai menapaki
padatan-padatan kata yang dikabarkan. Sebab, puisi tak pernah berhenti
pada selesainya penyair mengakhiri kata dalam baitnya. Akan tetapi,
bait-baitnya itu akan berkelanjutan: menemukan ruhnya sendiri ketika
selesai ditulis.
*Kaha Anwar
Anggota Teater Magnit Ngawi angkatan ke-10 dan sekarang tinggal di Yogyakarta I Sumber






 I. Pendahuluan
I. Pendahuluan